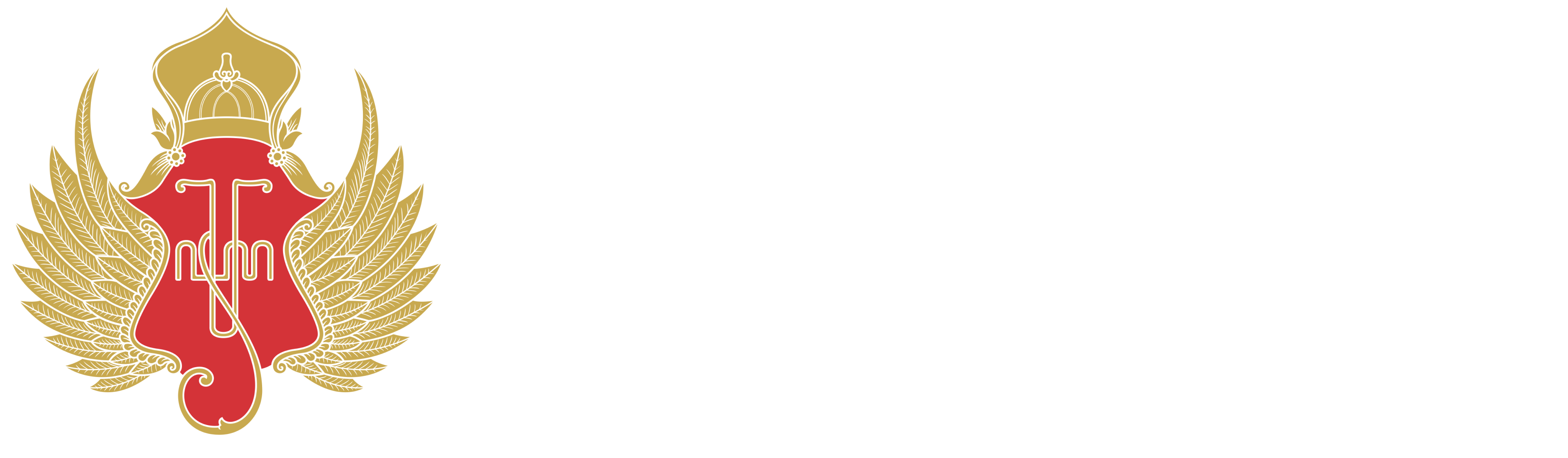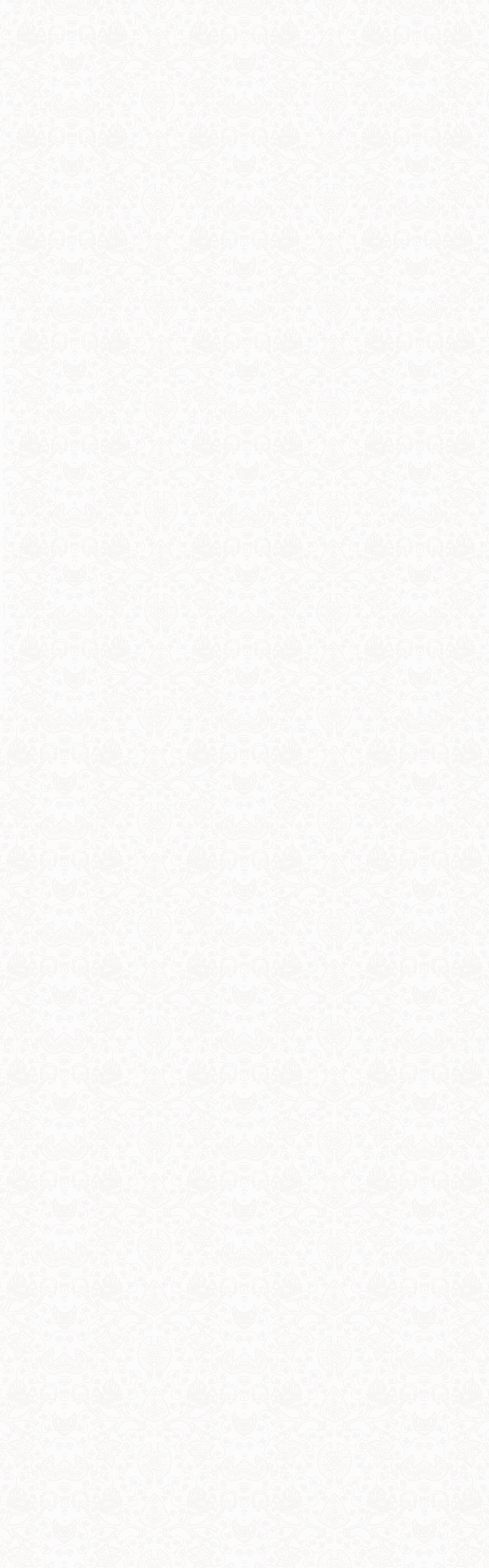KRT Pujaningsih, Sang Penjaga Tari Pusaka

Nyi KRT Pujaningsih
Keraton Yogyakarta memiliki pusaka berharga yang tak terhitung banyaknya. Pusaka-pusaka itu tak hanya berupa materi ragawi, namun juga intangible asset, seperti karya seni. Tari klasik yang diciptakan secara khusus oleh raja-raja dan bangsawan Jawa di masa lampau adalah salah satunya. Tari-tari adiluhung tersebut begitu rumit sehingga tak sembarang penari dapat membawakannya, apalagi memahami nilai historis dan filosofisnya. Pelestarian pusaka semacam ini menjadi tugas sejarah bagi keberlangsungan pusaka itu sendiri.
KRT Pujaningsih mencintai tari sejak belia. Kini, di usianya yang sudah berkepala tujuh, ia menjadi salah satu dari beberapa penjaga warisan budaya tersebut. Perempuan yang bernama asli Theresia Suharti ini bertugas sebagai pamucal –pengajar- tari di keraton. Namun, pengabdiannya pada tari sudah dimulai jauh sebelum itu.
Menghidupi Tari dan Hidup dari Tari
Begitu lulus SMP, Suharti melanjutkan pendidikan ke Konri (Konservatori Tari, kelak menjadi SMKI) dan begitu lulus ia diminta mengajar di sana. “Saya merasa sangat kurang, karena baru lulus kok disuruh mengajar,” kenangnya, “tapi saya tak bisa menolak karena dipaksa keadaan.” Waktu itu kebetulan guru tari dari Keraton Surakarta tak dapat mengajar rutin hingga Suharti harus menggantikannya. “Banyak yang mengatakan (tari Surakarta dan Yogyakarta) susah dan banyak bedanya. Tetapi saya merasa tidak ada yang perlu dibedakan, sama saja.” Demi menambah ilmu, ia mengajukan syarat bahwa sembari mengajar ia ingin kuliah di ASTI (sekarang ISI).
Suharti menceritakan banyak orang mengoloknya saat ia bersekolah di Konri, “Sekolah kok sekolah joged? Mau jadi apa? Jadi ledek?” Ia menerima itu dengan pikiran positif dan malah bertekad kuat untuk membuktikan tari bisa menghidupi dan mengangkat derajatnya.
“Saya ingin membantu ayah ibu saya. Mereka bukan orang kaya. Kalau harus bikin baju (untuk menari), saya berusaha membuat sendiri.”
Sebagai salah satu siswa berprestasi, pada kelas satu Suharti ditunjuk menjadi anggota misi kesenian ke Filipina. Setelah itu permintaan untuk mengajar dan tampil dalam pertunjukan terus mengalir. Sewaktu kuliah, Suharti melanglang buana sebagai duta kesenian ke berbagai negara; Jerman, Finlandia, hingga Yugoslavia.
Pada bidang akademis, Suharti juga tidak berhenti. Setelah meraih gelar sarjana muda, ia terus kuliah hingga mencapai gelar doktor. Ia menulis banyak jurnal dan buku hingga menjadi narasumber di berbagai seminar. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen di Wesleyan University, Amerika Serikat.
Merekonstruksi Bedhaya Semang yang Sakral
Salah satu karya monumental Suharti adalah rekonstruksi Bedhaya Semang, tari sakral yang seabad lebih tidak ditarikan. Suharti bersama timnya berusaha merekonstruksi tarian yang berkisah mengenai pertalian kasih antara Sultan Agung dan Kanjeng Ratu Kidul ini. Untuk mewujudkannya, Suharti harus mempelajari manuskrip-manuskrip lama, termasuk notasi gendingnya. Beksa berdurasi empat jam ini akhirnya berhasil dipergelarkan di Keraton tahun 2002, tiga puluh tahun lebih sejak Suharti memulai penelitian mengenainya. Tim penari dan pengrawit memerlukan waktu untuk latihan selama dua tahun demi menampilkan tari yang hanya boleh ditampilkan di dalam istana ini.
Meneliti dan merawat beksa bedhaya seolah menjadi panggilan jiwa Suharti. Bedhaya Semang ia angkat sebagai topik penelitian skripsi untuk mencapai gelar sarjana muda dan disertasi. Selanjutnya Suharti diminta oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk meringkasnya sehingga dapat ditampilkan sesuai kondisi keraton saat ini. Kini, tari ini memiliki versi yang lebih pendek, dua jam saja.
Suharti tak hanya menggeluti Bedhaya Semang. Nyaris semua tari klasik gaya Mataraman ia kuasai, seperti Srimpi dan Golek. Tak sekadar menguasai gerakan, ia juga memahami sejarah, filosofi, notasi gending, hingga kostum. Ia dengan mudah menuturkan perbedaan tarian Yogyakarta dan Surakarta. Bila melihat suatu variasi pengembangan tari, ia langsung tahu tarian yang menjadi induknya.
Tari gaya Yogyakarta disebutnya lebih lugu dan memiliki sifat militeristik, sesuai karakter pendiri keraton Yogyakarta yang seorang pejuang, sementara Surakarta lebih bergaya romantik. Dengan segala pengetahuannya Suharti ibarat ensiklopedia tari klasik Mataraman, seorang maestro dan ilmuwan tari yang susah dicari tandingannya.
Kini, di usianya yang tak lagi muda, Suharti tak kehilangan vitalitasnya. Ia masih mampu menari di atas panggung, mengajar, serta menjadi nara sumber. Cara bertuturnya lembut, jernih, rinci, dan penuh humor. Ini karena menari menurutnya tak hanya mengolah jasmani, namun juga mengolah rasa.
“Mataya bermakna menari, tapi Taya dengan ‘T’ besar juga berarti Tuhan. Menari berarti menyatu dengan Tuhan, sama seperti doa. Itu tataran paling tinggi,” jelasnya. Penari sekarang menurutnya banyak yang hanya senang pentas dan mementingkan hapalan gerakan semata. “Kesungguhan dalam menari terlupakan dalam situasi serba cepat. Kalau belajar asal sudah hapal sudah, padahal kan (seharusnya) tidak sekadar hapal. Penghayatan itu penting sekali.”
Ia berharap kekayaan kesenian keraton yang begitu berharga akan lestari. “Sekarang banyak Abdi Dalem muda. Ini adalah hal yang menggembirakan. Saya tidak merasa sendirian. Ada penerus yang bisa diharapkan.” Ya, menjaga dan melestarikan pusaka memang bukan kerja satu dua orang saja.

PERISTIWA POPULER
- Pentas Wayang Wong Gana Kalajaya, Perkuat Hubungan Diplomatik Indonesia-India
- Peringati Hari Musik Sedunia, Keraton Yogyakarta Gelar Royal Orchestra dan Rilis Album Gendhing Soran Volume 1
- Talk Show: Kendhangan Ketawang Gaya Yogyakarta dan Launching Kendhangan Ketawang
- Bojakrama, Pameran Jamuan di Keraton Yogyakarta Usai Digelar
- Tetap Patuhi Prokes, Pembagian Ubarampe Gunungan Garebeg Besar Digelar Terbatas
PERISTIWA TERKINI
-
Cerita Terkini dari Abhimantrana
Peristiwa