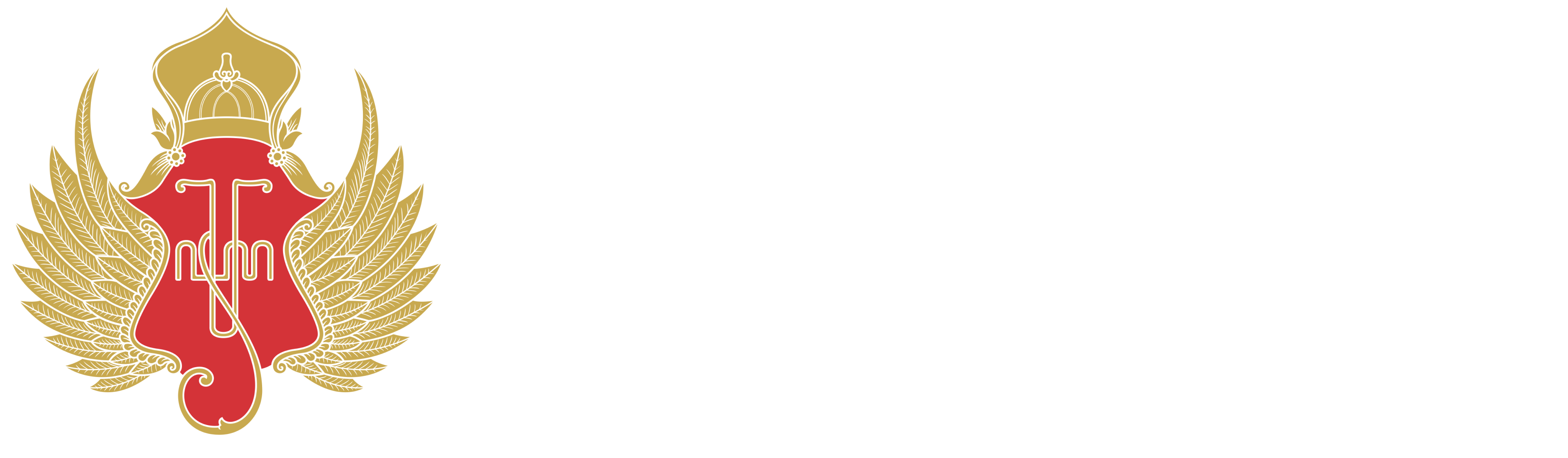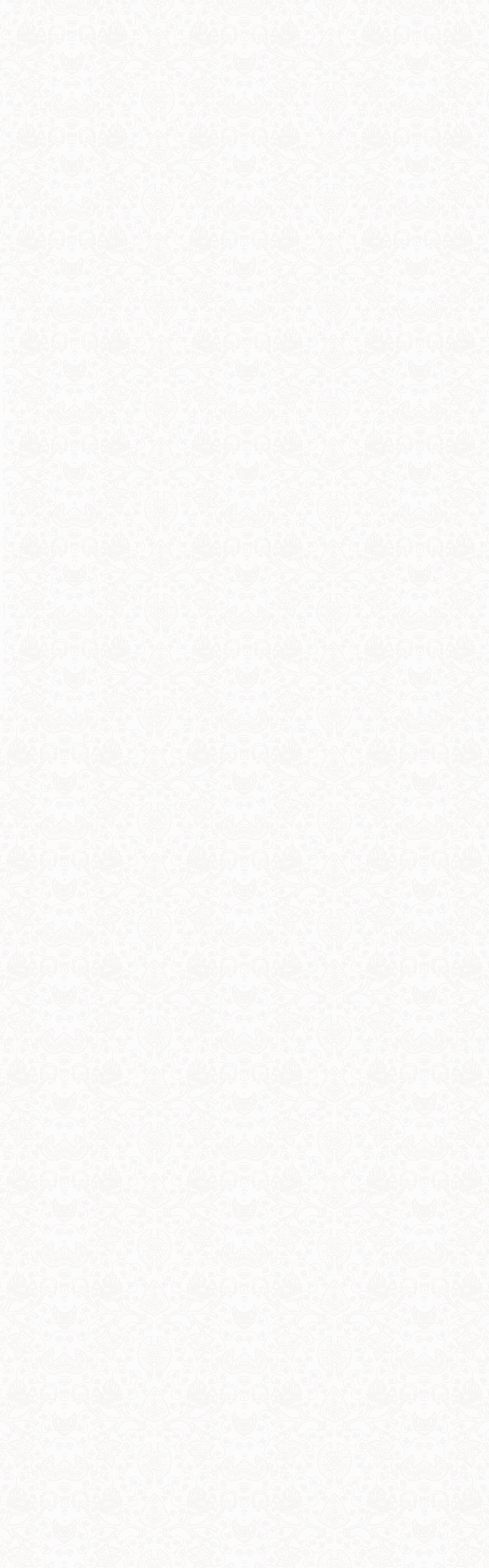Wayang Wong, Drama Tari Kenegaraan Keraton Yogyakarta
- 12-10-2021

Pertunjukan Wayang Wong yang disajikan secara lengkap adalah pertunjukan drama tari akbar. Pada masa puncaknya di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1239), sebuah pertunjukan Wayang Wong di Keraton Yogyakarta mampu melibatkan 300 sampai 400 penari, dipentaskan selama tiga sampai empat hari berturut-turut dari pukul 06.00 sampai 23.00 tanpa istirahat, menarik sekitar 30.000 penonton tiap harinya, menghabiskan biaya 15.000 gulden untuk produksi, dan 200.000 gulden untuk pembuatan busana. Sebagai perbandingan, gaji tertinggi seorang Abdi Dalem pada masa itu hanyalah 150 gulden sebulan.
Awal Mula Wayang Wong
Di Jawa, Wayang Wong atau Wayang Orang berkembang bersama dengan wayang kulit. Keduanya saling memengaruhi satu sama lain. Keberadaan drama tari yang mengisahkan cerita wayang telah disebutkan pada prasasti Wimalasmara di Jawa Timur yang berangka tahun 930 Masehi. Prasasti tersebut menyebutkan istilah wayang wwang. Dalam bahasa Jawa Kuno (Kawi), wayang berarti bayangan dan wwang berarti manusia.

Fragmen Wayang Wong Pregiwa, dokumentasi Kassian Cephas, Photography in the Service of The Sultan/KITLV
Drama tari yang berasal dari Mataram Kuno di Jawa Tengah ini kemudian dilestarikan oleh kerajaan-kerajaan penerusnya seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit. Ketika Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755, Sri Sultan Hamengku Buwono I (1755-1792) sebagai pendiri dan raja pertama Kesultanan Yogyakarta menggubah dan mencipta ulang kesenian tersebut. Di Yogyakarta, Wayang Wong ditempatkan pada posisi terhormat. Wayang Wong menjadi pertunjukan ritual kenegaraan dan untuk merayakan upacara-upacara penting seperti ulang tahun penobatan dan pernikahan anak Sultan.
Pergelaran Wayang Wong pertama di Yogyakarta diperkirakan diselenggarakan tahun 1757 dengan mengangkat lakon Gandawardaya, sebuah carangan (cabang cerita) dari kisah Mahabharata. Pada saat itu, pertunjukan masih menggunakan pola pertunjukan wayang kulit. Panggung berbentuk sempit tetapi panjang dan pergerakan pemainnya menggunakan pola dua dimensi.

Wayang Wong lakon Jaya Semadi, dokumentasi Kassian Cephas, Photography in the Service of The Sultan/KITLV
Perkembangan Wayang Wong
Sri Sultan Hamengku Buwono V (1823-1855) yang terkenal memiliki perhatian besar pada seni dan budaya memberi andil besar bagi perkembangan Wayang Wong. Bahkan terdapat babad yang menceritakan bahwa beliau ditemani oleh Pangeran Mangkubumi, adiknya yang kelak menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono VI, menari bersama dalam sebuah pertunjukan Wayang Wong. Pada masa pemerintahannya, Wayang Wong dipentaskan sedikitnya lima kali.
Pada masa ini pula dilakukan pengembangan penulisan Serat Kandha yang telah dimulai sejak era Sri Sultan Hamengku Buwono I. Serat Kandha adalah teks cerita yang dibacakan oleh pemaos kandha (pembaca cerita) dalam pertunjukan Wayang Wong.
Pada masa ini penari Wayang Wong diklasifikasikan menjadi tiga, ringgit gupermen, ringgit encik, dan ringgit cina. Kata ringgit berarti wayang, atau penari Wayang Wong. Gupermen berarti pemerintahan, mengacu pada kata dari Bahasa Belanda gouverment yang diucapkan dengan lidah Jawa. Encik berarti orang Timur Asing, merujuk ke warga negara asing non-Eropa. Cina merujuk kepada orang-orang berkebangsaan Cina.

Wayang Wong lakon Jaya Semadi, dokumentasi Kassian Cephas, Photography in the Service of The Sultan/KITLV
Klasifikasi ini kemungkinan dibuat untuk membagi Wayang Wong berdasar kualitas dan lokasi pertunjukan. Ringgit gupermen digelar di Tratag Bangsal Kencana dan digunakan sebagai upacara kenegaraan yang biasa dihadiri oleh kalangan istana serta orang-orang Belanda di pemerintahan. Ringgit encik digelar di Bangsal Trajumas. Sedang ringgit cina yang memiliki kualitas penari paling rendah digelar di Bangsal Kemagangan. Klasifikasi ini sejalan dengan hierarki sosial pada masa itu yang menempatkan orang-orang Belanda dan istana di lapisan pertama, orang-orang Arab dan India di lapis kedua, dan orang-orang Cina di lapisan paling bawah.
Pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921), pertunjukkan Wayang Wong diperlengkap dengan Serat Pocapan. Serat Pocapan adalah teks dialog dari masing-masing tokoh yang dipentaskan. Teks ini tidak dibawa saat pentas, namun hanya digunakan saat latihan saja.
Pada tahun 1918, dua putra Sri Sultan Hamengku Buwono VII, GPH Tejokusumo dan BPH Suryodiningrat, mendirikan perkumpulan Kridha Beksa Wirama. Perkumpulan ini menandai keluarnya ilmu tari dari dalam benteng keraton. Sebagai imbas dari kebijakan ini, banyak masyarakat yang menguasai tari keraton dan persediaan penari untuk pementasan Wayang Wong makin bertambah banyak.
Perkembangan Wayang Wong mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), bahkan beliau dikenal sebagai pelindung besar Wayang Wong. Pada masa ini, ada sebelas pertunjukan Wayang Wong yang digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintaraga dan Samba Sebit yang digelar selama empat hari untuk merayakan perkawinan beberapa putri Sultan.
Berbagai pembaruan dilakukan pada masa ini. Tata busana dirancang mengacu pada pakaian yang digunakan karakter di wayang kulit. Pada masa sebelumnya busana penari banyak dipinjam dari pakaian prajurit. Karakterisasi para tokoh juga disempurnakan, termasuk kelengkapan pentas yang dibuat menjadi lebih realis. Selain itu, dilakukan juga penciptaan gerak khusus bagi tokoh-tokoh kera. Bahkan pergelaran yang sebelumnya hanya dilakukan sampai sore pukul 18.00, diperpanjang sampai pukul 23.00 karena telah munculnya penerangan dari listrik.
Selepas pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), Wayang Wong di Keraton Yogyakarta mengalami kemunduran. Berkecamuknya Perang Dunia II dan masa pendudukan Jepang memperburuk kondisi keraton dan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Sejak saat itu, tidak ada lagi pementasan Wayang Wong secara besar-besaran. Namun begitu, Wayang Wong tetap lestari walau hanya dipentaskan dalam fragmen-fragmen pendek oleh perkumpulan-perkumpulan dan sekolah tari. Bahkan Kridha Beksa Wirama membawa pertunjukkan ini ke luar keraton dan mulai menampilkan penari putri untuk membawakan tokoh-tokoh putri. Sebelumnya, seluruh peran Wayang Wong dibawakan oleh penari pria, baik itu tokoh putra maupun tokoh putri.

Pertunjukan Wayang Wong lakon Gandawardaya di Bangsal Pagelaran, November 2019.
Peran Wayang Wong bagi Keraton Yogyakarta
Bagi Keraton Yogyakarta, Wayang Wong bukan sekadar pertunjukan kesenian belaka. Sebagai ritual kenegaraan, Wayang Wong merupakan sarana legitimasi kekuasaan. Mencipta kembali dan mementaskan Wayang Wong tidak lama setelah berdirinya kesultanan yang baru dapat diartikan sebagai salah satu upaya Sri Sultan Hamengku Buwono I menunjukkan keabsahannya sebagai penerus raja-raja Jawa.
Sebagaimana tari gaya Yogyakarta yang lain, belajar dan berlatih Wayang Wong juga merupakan sarana pendidikan jiwa dan tata krama. Tidak heran apabila banyak peran-peran penting dalam pementasan Wayang Wong dimainkan oleh putra-putra Sultan sendiri. Bahkan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII selalu menasehati putra-putranya untuk mengasah kemampuan menari.
Bahkan ketika pemerintah kolonial makin menekan Kesultanan Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, keraton menggunakan Wayang Wong sebagai strategi kebudayaan dalam menghadapi tekanan tersebut. Karena terhimpit secara militer dan politik administratif, Sultan menggelar banyak pementasan Wayang Wong secara akbar untuk menunjukkan kebesarannya sebagai seorang raja.
Daftar Pustaka:
Dewan Kesenian Propinsi DIY. 1981. Mengenal Tari Klasik Gaya Yogyakarta. Yogyakarta: Departemen P & K.
Pramutomo, RM. 2009. Tari, Seremoni, dan Politik Kolonial I & II. Solo: ISI Press.
Soedarsono, RM. 1997. Wayang Wong: Drama Ritual Kenegaraan di Keraton Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Susanto. 1996. Wayang Wong dan Tahta, Suatu Kajian Tentang Politik Kesenian Hamengku Buwono VIII 1921-1939. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Wibowo, Fred. 2002. Tari Klasik Gaya Yogyakarta. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.